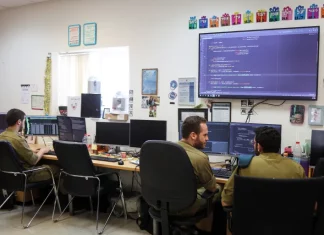Dalam gelap malam, warga Gaza terbangun oleh suara kota yang “dikunyah” dan ditelan sedikit demi sedikit oleh Israel. Siang harinya, mereka dikejar kabar tentang makar baru, peta baru, dan garis waktu untuk merebut sisa-sisa tanah yang masih bertahan. Lebih dari satu juta orang kini terhimpit dalam wilayah tak lebih dari 20% dari luas asli Gaza dan sekitarnya.
Antara malam yang merampas ruang hidup dan siang yang menguapkan harapan, Israel menjalankan rencana pengusiran terang-terangan di depan mata dunia: menghancurkan Gaza, mendudukinya, dan menyingkirkan penghuninya. Warga pun dipaksa mengungsi demi menyelamatkan nyawa anak-anak dan diri mereka, meski setiap langkah ditemani hujan api.
Mengungsi di Bawah Serangan
Di persimpangan Jalan al-Jalaa, ratusan warga dari Jabaliya, al-Saftawi, dan Sheikh Radwan terlihat berbondong-bondong. Mereka berlari di bawah gempuran artileri dan tembakan drone Israel yang memburu siapa saja yang masih bertahan.
Dari kejauhan, tampak seorang perempuan hamil berlari dengan memikul karung tepung di pundaknya. “Mereka bahkan menganggap kami tak pantas mendapat selembar tenda usang di atas reruntuhan rumah kami, di samping tempat sampah,” katanya dengan napas terengah. “Apakah ada perempuan di dunia ini, yang menjelang melahirkan, harus berlari sambil memanggul karung tepung?”
Pemandangan itu seperti hari kiamat. Laki-laki mendorong gerobak dengan harta seadanya, perempuan memanggul rumah yang runtuh dalam tas di punggung, anak-anak berlari hanya membawa sebotol air dan seikat kayu bakar. Semua mencari sejengkal ruang yang tak dijangkau Israel.
“Keluar dengan abaya saja, tanpa sempat bawa apa-apa,” kata Ummu Muhammad al-Batsh yang berhenti sejenak melepas lelah. “Kapan berakhir pengusiran tanpa henti ini?”
Namun arah tujuan para pengungsi memperlihatkan sikap tegas. Meski Israel memerintahkan warga menuju selatan, banyak yang justru memilih barat, ke arah laut. “Kami tidak mau ke selatan,” ujar seorang pria tua yang menarik barang bawaan lebih berat dari tubuhnya.
Ilusi “Zona Aman”
Biaya mengungsi terlalu mahal. Untuk mencapai wilayah selatan dan menyewa sebidang tanah, satu keluarga memerlukan lebih dari 2.000 dolar. “Uang 50 dolar saja saya tidak punya,” kata seorang pengungsi di pelabuhan Gaza dengan tawa getir.
Dan bagi yang berhasil sampai, janji keamanan Israel hanyalah ilusi. Di Khan Younis, sebuah keluarga pengungsi dari Jabaliya tewas sekeluarga dihantam serangan udara Israel hanya dua hari setelah mendirikan tenda.
“Kami kira selatan itu aman, ternyata hanya jebakan,” kata ibu korban, penuh penyesalan. “Tak ada yang namanya zona aman.”
Husam Ahmad, seorang pengungsi yang sempat mencoba jalur “aman” yang ditandai di peta Israel, akhirnya kembali ke Gaza. “Lokasi itu entah penuh sesak dengan tenda, di dekat markas militer Israel, atau di lahan tak layak—tempat sampah dan kolam limbah,” katanya. “Lebih baik mati di rumah sendiri daripada hidup dalam kehinaan.”
Laut: Harapan Terakhir
Kini, warga Gaza menatap ke arah barat, menjadikan laut sebagai batas terakhir yang masih terbuka. Di sana mereka mendirikan tenda seadanya, mencoba menggantungkan harapan pada ufuk biru yang belum dipagari tentara.
Namun mereka sadar, langkah menuju selatan bisa berarti “perjalanan tanpa pulang.” Mengungsi bukan lagi sekadar perpindahan sementara, melainkan ujian harian mempertahankan hidup. Gaza tak hanya dirampas dari tangan mereka, tetapi juga dari ingatan dan sejarah mereka.
Bagi warga Gaza, bertahan di tanah leluhur meski di ambang bahaya adalah pilihan terakhir yang lebih bermartabat daripada menyerah pada ilusi keselamatan.
Sumber: Al Jazeera