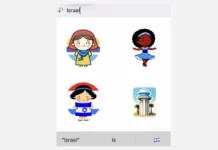Di atas ranjang besi usang di Rumah Sakit Pemerintah Syuhada Al-Aqsa (satu-satunya rumah sakit di wilayah tengah Jalur Gaza) Mahamud Said, pemuda 26 tahun, terbaring tak berdaya. Ia tak sanggup bergerak, kedua kakinya terpasang pen penahan tulang akibat diterjang delapan peluru pasukan Israel saat mencoba mendapatkan bantuan pangan di Rafah, selatan Gaza.
“Setiap hari aku berjalan jauh untuk mencari makanan. Kini, ke kamar mandi saja aku butuh bantuan empat orang,” ujarnya kepada Al Jazeera. Keputusasaan akibat kelaparan sembilan anggota keluarganya mendorongnya mengambil risiko besar demi mengantre bantuan. Namun alih-alih membawa pulang makanan, Said justru pulang sebagai korban luka tembak.
Sejak pembukaan pusat distribusi bantuan yang disokong AS dan Israel pada 27 Mei lalu, titik-titik itu dijuluki warga sebagai “jebakan maut”. Data resmi Palestina menyebutkan lebih dari 900 orang tewas, 6.000 luka-luka, dan 42 lainnya hilang saat berusaha mengakses bantuan di sana.
Luka Tanpa Obat, Rasa Sakit Tanpa Jawaban

Delapan peluru yang bersarang di kaki Said membuat tulangnya hancur dan ia menderita kesakitan luar biasa. Para dokter berusaha semampunya, tetapi keterbatasan obat-obatan dan alat medis membuat pengobatan nyaris mustahil. Bahkan makanan pun tidak tersedia bagi pasien dan tenaga medis.
Sebelum perang meletus pada 7 Oktober 2023, Said bekerja sebagai sopir taksi. Ia kehilangan pekerjaannya dan terpaksa mengungsi lebih dari 20 kali. Kini, ia tak tahu bagaimana nasibnya dengan kondisi rumah sakit yang kolaps dan minim sumber daya.
Di ruangan lain, Janna Al-Nusairat, gadis 13 tahun, terbaring dengan luka parah setelah serangan udara menghantam rumah yang ia kunjungi di Deir Al-Balah. Ia menderita patah tulang di keempat anggota tubuhnya serta luka bakar di wajah dan tubuh. Minimnya salep luka dan peralatan medis memperparah penderitaannya.
Lonjakan Jumlah Penyandang Disabilitas

Menurut Dr. Iyad Al-Kurnaz, Koordinator Kantor Gaza di Kelompok Kerja Disabilitas, perang telah meningkatkan jumlah penyandang disabilitas sebesar 55 persen, sebagian besar berupa disabilitas fisik akibat amputasi. Sebelum perang, terdapat 58.000 orang penyandang disabilitas, kini bertambah 32.000 orang lagi. Data WHO menunjukkan bahwa 25 persen korban luka mengalami disabilitas permanen.
Laporan terbaru bersama Save the Children menunjukkan bahwa 10 anak kehilangan kaki setiap harinya di Gaza. Kini, terdapat sekitar 90.000 penyandang disabilitas dan 107.000 lansia dengan penyakit kronis yang hidup tanpa akses obat, 3.800 di antaranya meninggal dunia karena hal itu.
Israel melarang masuknya alat bantu disabilitas seperti kursi roda dan tongkat dengan alasan bisa disalahgunakan untuk tujuan militer. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi sistematis untuk memperburuk kondisi kelompok rentan.
Runtuhnya Sistem Kesehatan Gaza
Lebih dari 80 persen pusat rehabilitasi telah hancur atau tak lagi berfungsi, termasuk Rumah Sakit Sheikh Hamad untuk Rehabilitasi dan Ortopedi. Penyandang disabilitas kini tak mendapatkan terapi fisik yang layak dan hidup di pengungsian yang tidak ramah terhadap kebutuhan mereka.
Menurut Dr. Marwan Al-Homs dari Kementerian Kesehatan Gaza, banyak layanan medis krusial kini lumpuh total: 99 persen layanan bedah jantung, 85 persen bedah tulang, 54 persen layanan kanker, dan hampir separuh layanan cuci darah kini tidak bisa dijalankan.
Dengan keterbatasan sumber daya, rumah sakit terpaksa menerapkan sistem “triase krisis”: hanya pasien dengan peluang selamat yang diutamakan, sementara yang kritis dibiarkan menunggu ajal.
Dalam sistem yang rusak akibat pemboman dan blokade, ribuan pasien luka dan kronis kehilangan hidup dan anggota tubuh mereka, padahal bisa diselamatkan jika sumber daya dan tenaga medis mencukupi. Perang di Gaza tak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengikis hak dasar manusia untuk bertahan hidup.